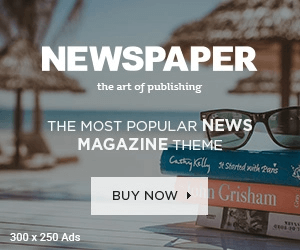Belakangan ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan institusi keagamaan (Ormas) yang mendapat izin dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk mengelola tambang. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah beralasan bahwa pemberian izin ini bertujuan agar ormas keagamaan dapat menjadi lebih mandiri. Beberapa memandang ini sebagai sesuatu yang lumrah, sebab sama saja dengan lembaga-lembaga lain seperti PT (Perseroan Terbatas).
Penulis teringat ketika zaman Joseph Stalin, yang memerintah akhir 1920-an hingga kematiannya pada tahun 1953, dikenal dengan para penjilat yang memuji kebijakannya dan melaporkan orang-orang yang dianggap sebagai musuh negara. Orang atau kelompok yang setia dan berjasa dalam menjaga kekuasaannya pasti dihadiahi jabatan tinggi dan berbagai keuntungan lainnya. Pun di Eropa ketika itu pemerintahan Kaisar Nero di Roma kuno. Nero, yang memerintah dari tahun 54 hingga 68 M, dikenal karena ketidaksabarannya terhadap kritik dan kecenderungannya memberi hadiah kepada orang-orang yang memujinya. Para penjilat di istananya sudah pasti mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh sebagai imbalan atas kesetiaan dan kesiapan mati untuk penguasa.
Meminjam gagasan Michel Foucault, bahwa kekuasaan dan pengetahuan selalu terkait erat. Lembaga keagamaan, dengan otoritas spiritual, memasuki ranah ekonomi melalui pengelolaan tambang, mengklaim pengetahuan dan keahlian di bidang yang sebenarnya teknis dan sekuler. Hal ini kemudian menciptakan hibriditas otoritas yang dapat melegitimasi tindakan ini, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan di tsanawiyah dan aliyah. Tesisnya adalah keterlibatan lembaga keagamaan dalam bisnis tambang merupakan penyalahgunaan kekuasaan, di mana kemudian menggunakan otoritas spiritual untuk melegitimasi tindakan yang didorong oleh motif ekonomi pragmatisme.
Langkah ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini nantinya siap menggunakan otoritas spiritual untuk mencapai tujuan ekonomi. Ini bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga sangat mengkhianati kepercayaan umat. Mengapa? Bagaimana bisa lembaga yang seharusnya menjadi penuntun moral malah terlibat dalam aktivitas ekonomi yang merusak dan eksploitatif alam dan manusia?
Ketika lembaga keagamaan terlibat dalam pengelolaan tambang, mereka mengadopsi identitas baru yang terkait erat dengan kapitalisme dan eksploitasi sumber daya alam. Transformasi ini dapat merusak citra lembaga keagamaan sebagai penjaga moralitas dan spiritualitas. Identitas baru ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas lembaga keagamaan dan dapat mengurangi kepercayaan umat yang melihat mereka sebagai entitas ekonomi daripada entitas spiritual. Iya memang sih ekonomi itu sebagai penunjang jalannya roda organisasi, tapi tidak juga dengan menambang bumi, kan masih bisa jual es teh dan es buah!
Mau tidak mau keterlibatan lembaga keagamaan dalam bisnis tambang menunjukkan perubahan identitas nantinya meskipun tidak secara administratif tertera dalam AD/ART Lembaga. Mengapa? Sebab mereka bukan lagi institusi yang berdiri di atas prinsip moral dan etika, melainkan entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini jelas menciptakan dilema bagi umat yang mungkin mulai meragukan integritas dan tujuan sebenarnya dari lembaga ini.
Manipulasi Praktik Diskursif
Postrukturalisme melihat bagaimana praktik diskursif membentuk realitas dan legitimasi. Lembaga keagamaan menggunakan narasi yang membingkai pengelolaan tambang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan organisasinya atau memanfaatkan sumber daya alam untuk lembaganya. Namun, ini bisa dilihat sebagai alat untuk menutupi motif ekonomi yang sebenarnya. Praktik diskursif semacam ini dapat menghindari kritik dan mempertahankan kontrol atas narasi publik, mengaburkan tujuan ekonomi di balik topeng misi sosial.
Narasi yang digunakan oleh lembaga keagamaan untuk membenarkan keterlibatan mereka dalam bisnis tambang menciptakan ilusi bahwa tindakan ini adalah demi kebaikan bersama. Namun, jika kita menggali lebih dalam, motif ekonomi yang sebenarnya menjadi sangat jelas. Penggunaan praktik diskursif semacam ini adalah bentuk manipulasi yang licik, yang bertujuan untuk mengelabui publik dan menghindari kritik.
Uraian di atas mengafirmasi bagaimana struktur paling atas, sebut saja Pengurus Besar (PB), akan melakukan tindakan sewenang-wenang dan sepihak. Mengapa PB? Sebab di tataran paling bawah penulis yakin masih memiliki iman (idealisme), sedangkan hierarki paling atas sering mengabaikan visi institusi. Bayangkan besok mereka menambang bumi, ada dua hal yang terkabur dari realitas, hal pokok: etika lingkungan dan keadilan sosial. Padahal jelas pengelolaan tambang berdampak negatif pada ekosistem, mengotori sumber air, dan merampas hak-hak masyarakat lokal. Keterlibatan lembaga keagamaan dalam bisnis tambang menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip etika lingkungan dan keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Pergeseran nilai di mana keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat adalah bukti nyata dari degradasi moral.
Etika lingkungan adalah salah satu prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga keagamaan. Namun, dengan terlibat dalam bisnis tambang, hal ini kemudian menunjukkan bahwa mereka secara tidak langsung siap mengorbankan prinsip ini demi keuntungan ekonomi.
Dampak negatif dari aktivitas penambangan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal adalah nyata. Harusnya lembaga keagamaan melihat dan mengambil pelajaran dari kerusakan penambangan bumi di negeri ini. Penambangan di Morowali telah mengakibatkan deforestasi masif dan pencemaran air yang parah. Limbah tambang yang mengalir ke sungai bukan hanya merusak ekosistem air, tetapi juga meracuni sumber air bersih yang sangat vital bagi masyarakat setempat. Ironisnya, kesejahteraan yang dijanjikan dari hasil tambang ini justru menambah penderitaan penduduk sekitar akibat rusaknya lingkungan tempat mereka bergantung.
Hal yang sama terjadi juga di Jawa Barat, penambangan di Gunung Pongkor memperlihatkan wajah lain dari bencana lingkungan. Penggunaan merkuri dalam proses penambangan emas oleh penambang besar maupun liar menimbulkan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Merkuri, yang terkenal sebagai bahan kimia beracun, mencemari sungai-sungai yang menjadi sumber air dan penghidupan masyarakat, menambah daftar panjang bencana lingkungan yang disebabkan oleh keserakahan.
Bergeser ke Kalimantan Timur, penambangan batubara di Samarinda dan Kutai Kartanegara menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Deforestasi yang tidak terkendali, degradasi lahan, dan pencemaran air sungai adalah dampak nyata dari aktivitas tambang yang masif. Kolam-kolam bekas tambang yang tidak direklamasi dengan baik menjadi sarang penyakit, mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekitar. Tidak bisa dipungkiri, keuntungan besar yang diraup perusahaan tambang tidak sebanding dengan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat lokal.
Terakhir, di Tumpang Pitu, Banyuwangi, penambangan emas telah mengorbankan hutan lindung dan kawasan pesisir. Penggunaan bahan kimia beracun dalam proses penambangan tidak hanya mencemari air tanah dan laut, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar dan ekosistem laut yang rapuh. Kerusakan ini menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh lingkungan dan manusia akibat aktivitas penambangan yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak lagi contoh lain rentetan penambangan yang merusak di negeri ini.
Melihat contoh-contoh ini, harusnya lembaga keagamaan menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat harus menjadi prioritas utama. Pergeseran nilai di mana keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat mencerminkan hipokrisi yang terjadi dalam lembaga-lembaga ini. Mereka yang seharusnya menjadi contoh moralitas justru menunjukkan bahwa mereka tidak berbeda dari entitas bisnis yang mereka kritik. Ini adalah bukti nyata bahwa spiritualitas dan etika telah dikorbankan di altar kapitalisme.
Hipokrisi ini menjadi sangat jelas ketika kita melihat bagaimana lembaga-lembaga ini menggunakan retorika moral dan etika untuk membenarkan tindakan mereka, sementara pada saat yang sama terlibat dalam aktivitas ekonomi yang merusak. Ini adalah contoh dari bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan dan bagaimana prinsip-prinsip moral dapat dikorbankan demi keuntungan finansial. Lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi penuntun moral justru menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya sebagai agen kapitalisme.
Akhirnya, opini ini menegaskan bahwa keterlibatan lembaga keagamaan dalam pengelolaan tambang adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai spiritual yang mereka klaim junjung tinggi. Dengan memanipulasi diskursus publik dan mengabaikan etika lingkungan serta keadilan sosial, lembaga-lembaga ini telah menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya: entitas ekonomi yang menggunakan kedok spiritualitas untuk mengejar keuntungan.
Umat dan masyarakat harus membuka mata terhadap realitas ini dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari lembaga-lembaga yang seharusnya memimpin dengan contoh moral yang tinggi. Saatnya untuk menyerukan kembalinya lembaga keagamaan ke jalan yang diridhai Tuhan, di mana moralitas dan etika diutamakan daripada keuntungan ekonomi. Lembaga keagamaan harus mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam bisnis tambang dan fokus pada peran mereka sebagai penuntun moral dan spiritual bagi umat.
Dengan demikian, penulis mengajak kita semua untuk menilai kembali peran dan tanggung jawab lembaga keagamaan dalam konteks yang lebih luas dan kompleks. Kita harus memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tetap setia pada misi dan nilai-nilai yang asli, dan tidak terjerumus ke dalam godaan kapitalisme yang merusak. Umat berhak bersuara lebih lantang bahwa lembaga keagamaan harus benar-benar berfungsi sebagai penjaga moralitas dan spiritualitas, bukan sebagai entitas ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan.