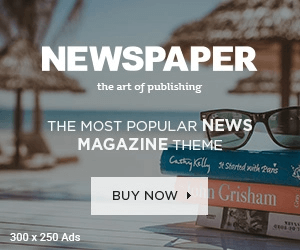Tanggal 1 Juni 2025 datang lagi, dan seperti biasa, layar televisi, spanduk pinggir jalan, dan caption Instagram para pejabat mendadak penuh kutipan Bung Karno. Ada yang menyontek dari Google, ada yang copas dari tahun lalu. Semua bicara tentang Pancasila, seolah-olah lima sila itu sedang baik-baik saja duduk di singgasana kebangsaan.
Padahal, andai Pancasila bisa bicara, barangkali ia akan berteriak, “Lepaskan aku dari pidato seremonial dan turunkan aku ke kehidupan nyata!”
Mari kita bersikap jujur. Di tahun 2025 ini, Pancasila semakin menyerupai mantra kuno yang dipuja dalam upacara, tetapi jarang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih menyaksikan Pancasila dibacakan dengan suara lantang di sekolah dan kantor pemerintahan, dada ditepuk, tangan memberi hormat. Namun setelah itu hidup dalam realitas yang justru menampar lima sila itu satu per satu.
Kini, 2025 sudah separuh jalan. Dunia makin riuh dan Indonesia pun tak luput dari kebisingan itu. Tetapi, harapan tidak pernah benar-benar padam. Ia hidup bukan dari mereka yang hanya pandai membacakan, melainkan dari mereka yang memilih hidup sebagai perwujudan Pancasila. Mereka yang tidak viral, tapi nyata.
Di tahun 2025 ini, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, Pancasila pun tampaknya kelelahan dibawa ke mana-mana tanpa pernah benar-benar diberi tempat tinggal yang layak. Mari kita tengok satu per satu.
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Secara konstitusional, sila pertama menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Kita sepakat pada Ketuhanan yang Maha Esa yang seharusnya memberi ruang pada seluruh umat beragama untuk menjalankan keyakinannya secara bebas, damai, dan bermartabat. Namun dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia masih sangat timpang.
Sila pertama bukan hanya soal beragama, tetapi juga soal menghormati perbedaan agama. Ketuhanan yang Maha Esa seharusnya menjadi fondasi keadilan spiritual di negeri ini, bukan justru alat pembenaran untuk diskriminasi terselubung.
Kita sering menyebut Indonesia sebagai negara yang religius. Tapi religiusitas tanpa penghormatan terhadap sesama justru melahirkan kepalsuan moral. Bukankah keimanan yang sejati selalu berbuah pada sikap adil terhadap sesama, tak peduli latar belakangnya?
Sila pertama sedang terluka. Ia tidak butuh dibela dengan pidato, tapi dipulihkan lewat perlakuan yang setara terhadap semua anak bangsa, apa pun keyakinannya. Tanpa itu, sila pertama hanyalah dekorasi ideologis di dinding-dinding sekolah dan kantor pemerintahan.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua berbicara tentang keadilan dan keberadaban sebagai asas hubungan antar manusia dalam kehidupan berbangsa. Dalam sila ini, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, memperlakukan warganya dengan martabat, dan menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari setiap kebijakan. Namun, apa yang terjadi di Indonesia hari ini justru berbanding terbalik dengan cita-cita luhur itu.
Kekerasan terhadap warga sipil masih terjadi dan sering dibungkam. Konflik agraria masih merajalela. Banyak warga desa tergusur atas nama “investasi strategis nasional”. Mereka kehilangan lahan, sumber kehidupan, bahkan sering kali tanpa ganti rugi yang memadai. Ketika melawan, mereka disebut “penghambat pembangunan”, bahkan ditangkap atau dibungkam. Kemanusiaan dikalahkan oleh uang dan kepentingan elite.
Selain itu, perlakuan hukum masih jauh dari adil. Hukum di Indonesia masih terlalu ramah pada orang kaya, dan terlalu garang pada orang miskin. Seorang pencuri kayu bakar bisa dipenjara, tapi koruptor miliaran bisa dipenjara sebentar lalu bebas dan tersenyum di depan kamera. Mereka yang membela hak rakyat, aktivis lingkungan, buruh, jurnalis independen, sering dikriminalisasi dengan pasal karet.
Apakah ini bentuk keadilan? Tentu tidak. Ini adalah pengkhianatan terhadap sila kedua.
Bukan hanya itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih sangat nyata. Menurut laporan terakhir, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi di Asia. Segelintir orang bisa makan malam di restoran langit dengan harga belasan juta, sementara jutaan lainnya bertarung di pasar demi sebungkus beras. Ini bukan hanya ketidakadilan ekonomi. Ini adalah pengingkaran terhadap martabat manusia.
Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk berhenti melihat rakyat sebagai angka statistik. Ia menuntut kepekaan, kesetaraan, dan keberanian untuk berpihak pada yang lemah. Tanpa itu, sila kedua hanya akan jadi bahan hafalan anak SD dan mati dalam praktik orang dewasa.
Jika bangsa ini benar-benar ingin disebut beradab, maka ukurannya bukan seberapa megah pembangunan, tapi seberapa manusiawi cara kita memperlakukan yang tertindas. Karena kemajuan tanpa kemanusiaan hanyalah kemewahan tanpa ruh.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Sila ketiga berbicara tentang persatuan. Kata yang tampaknya indah, suci, dan kerap diucapkan dalam orasi-orasi kebangsaan, bahkan menjadi lirik lagu wajib. Namun, dalam kehidupan sehari-hari bangsa ini, persatuan belum benar-benar hadir sebagai kenyataan sosial, ia masih lebih sering menjadi retorika daripada praktik.
Di Jakarta dan kota besar lainnya, kaum elite hidup dalam lingkaran eksklusif, penuh kenyamanan dan fasilitas. Sementara di pinggiran, warga harus berjuang keras dengan ketidakpastian ekonomi, pendidikan terbatas, dan akses kesehatan yang timpang.
Indonesia yang dimaksud dalam sila ketiga, kadang hanya terasa milik mereka yang tinggal di pusat-pusat kekuasaan, yang di pinggiran hanya ikut numpang sebut nama. Bagaimana kita bisa bicara soal “persatuan Indonesia” kalau kenyataan sehari-harinya menunjukkan keterpisahan sosial yang begitu dalam?
Sila ketiga seharusnya mengingatkan kita bahwa Indonesia ini bukan milik satu golongan, satu suku, atau sekelompok elite. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan jiwa besar.
Sila Keempat: Kerakyatan atau Kepentingan?
Sila keempat bukan hanya tentang pemilu lima tahun sekali. Ia adalah ajaran luhur bahwa kekuasaan adalah amanat, bukan hak istimewa. Bahwa wakil rakyat harus benar-benar mewakili, dan keputusan politik harus lahir dari kebijaksanaan kolektif, bukan nafsu kekuasaan. Tanpa itu, demokrasi kita hanya akan menjadi panggung drama elit, bukan wadah perjuangan rakyat.
Sila keempat adalah ruh dari demokrasi Indonesia. Ia bicara tentang rakyat sebagai sumber kekuasaan, yang diwakili oleh orang-orang yang dipilih secara sah, dan yang seharusnya mengambil keputusan berdasarkan hikmat dan musyawarah. Tapi mari jujur. Apakah yang kita saksikan hari ini benar-benar kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, atau sekadar perwakilan yang dikendalikan oleh kepentingan?
Di balik meja rapat, permusyawaratan sering kali bukan soal adu gagasan, tapi adu kuasa dan sumber daya. Proses legislasi dan pengambilan kebijakan sering diwarnai oleh lobi-lobi politik, kompromi pragmatis, dan, tidak jarang, praktik transaksional yang mengabaikan kepentingan publik. “Musyawarah” hanya menjadi topeng sopan bagi keputusan yang sudah dikunci sebelumnya.
Kerakyatan bukan soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi bagaimana mereka bersikap kepada rakyat. Permusyawaratan bukan tentang banyaknya rapat, tapi seberapa jujur dan terbukanya proses pengambilan keputusan.
Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Elite Pejabat
Sila kelima adalah puncak dari seluruh sila sebelumnya. Ia bukan hanya tujuan, tapi ukuran, apakah negara benar-benar berpihak pada seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali? Apakah kekayaan negeri ini dinikmati bersama, atau hanya oleh segelintir orang? Hari ini, mari kita jujur, keadilan sosial di Indonesia masih lebih banyak berupa mimpi kolektif daripada realitas yang terasa.
Menurut data terakhir, 1% penduduk Indonesia menguasai lebih dari 40% kekayaan nasional.
Sementara itu, jutaan rakyat kecil, buruh, petani, nelayan, pekerja informal, harus berjibaku dari fajar hingga malam demi bertahan hidup.
Kita menyebut negeri ini kaya sumber daya alam, tapi rakyat yang tinggal di sekitar tambang dan hutan justru hidup dalam kemiskinan struktural. Kekayaan alam mengalir ke kota dan keluar negeri, sementara desa tetap tertinggal dalam keterbatasan.
Lebih dari itu, keadilan sosial tidak hanya bicara soal ekonomi, tapi juga keadilan dalam penegakan hukum. Namun kita masih menyaksikan pemandangan klasik, rakyat kecil dihukum berat karena pelanggaran ringan, sementara koruptor kelas kakap bisa bebas lebih cepat dengan berbagai “jalan pintas” hukum. Ketika rakyat tak lagi percaya pada hukum, maka keadilan sosial hanya menjadi jargon yang hambar.
Sila kelima tidak dimaksudkan sebagai belas kasihan dari yang kuat kepada yang lemah.
Ia adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk hidup layak, untuk diperlakukan adil, untuk tidak dibiarkan tertinggal.
Keadilan sosial bukanlah soal bagi-bagi bansos menjelang pemilu, tetapi soal menciptakan sistem yang memanusiakan semua, bukan hanya yang mampu bersuara. Jika sila kelima benar-benar dilaksanakan, maka tak akan ada lagi rakyat yang merasa asing di tanah airnya sendiri. Kita akan menjadi bangsa yang bukan hanya besar dalam angka, tapi juga dalam nurani.
Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan cermin nurani bangsa. Di tengah realita yang kerap jauh dari ideal, lima sila itu tetap menjadi kompas moral yang mengingatkan kita bahwa Indonesia layak diperjuangkan, bukan hanya diperingati. Jika kita ingin Pancasila hidup, maka keadilan, kemanusiaan, dan persatuan harus benar-benar terasa di nadi rakyat, bukan sekadar dalam pidato kenegaraan setahun sekali.