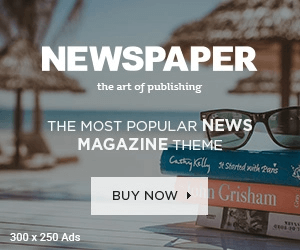“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
-Nelson Mandela-
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai bentuk penghormatan terhadap Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Namun, di tengah gegap gempita peringatan seremonial, kita patut merenung, apakah sistem pendidikan kita sudah menjawab tantangan zaman dan merangkul semua anak bangsa secara adil dan merata? Sejauh mana kita telah bergerak dari retorika menuju realita pendidikan yang adil dan berkualitas? Tahun 2025 menjadi momentum tepat untuk mengkritisi realitas pendidikan Indonesia yang masih diliputi masalah struktural dan ketimpangan.
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi nasional baru mencapai 36,31%. Ketimpangan makin nyata saat membandingkan antar wilayah: DKI Jakarta memiliki APK sebesar 71,9%, sementara Papua hanya mencapai 20,5%. Ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan ekonomi masih menjadi penghalang utama bagi akses pendidikan tinggi.
Selain itu, kualitas pendidikan juga belum memadai. Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-65 dari 81 negara dalam aspek literasi membaca dan matematika. Ini memperlihatkan bahwa walaupun partisipasi sekolah meningkat, kemampuan dasar siswa dalam memahami bacaan dan menyelesaikan persoalan matematika masih rendah.
Beban Administratif Guru dan Kurikulum yang Terlalu Ambisius
Guru sebagai ujung tombak pendidikan justru terbebani tugas administratif yang menggerus waktu dan energi untuk mengajar. Laporan Kemendikbudristek tahun 2023 mencatat bahwa 58% waktu kerja guru habis untuk mengisi laporan, membuat administrasi kelas, dan kegiatan birokratis lainnya. Hal ini berdampak langsung pada minimnya inovasi dalam proses belajar mengajar.
Sementara itu, Kurikulum Merdeka yang diluncurkan sejak 2022 memiliki semangat baik: memberi keleluasaan kepada sekolah dan guru. Namun dalam praktiknya, implementasi Kurikulum Merdeka tidak berjalan merata. Banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal, kekurangan sumber daya digital dan pelatihan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya memerdekakan justru menambah kebingungan di lapangan.
Ki Hajar Dewantara pernah berkata, “Guru itu bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing jiwa, pembentuk watak, dan penyemai budi pekerti”. Maka, sistem pendidikan yang membebani guru secara administratif jelas bertolak belakang dari visi luhur ini.
Komersialisasi dan Privatisasi Pendidikan
Isu lain yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya biaya pendidikan, bahkan di sekolah negeri. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya tahun 2024 menyebut bahwa lebih dari 35% sekolah negeri di kota-kota besar menerapkan pungutan yang tidak transparan kepada orang tua siswa. Padahal, pendidikan dasar seharusnya bebas biaya dan dapat diakses semua kalangan.
Privatisasi pendidikan juga mendorong kesenjangan antara sekolah elite dan sekolah biasa. Paulo Freire berkata “Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom.” Layanan pendidikan bermutu seolah hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara. Jika Pendidikan di analogikan sebagai “barang mewah” (dan memang begitu sejatinya), maka senjata perubahan itu tidak akan pernah jatuh ke tangan mereka yang memang dipersiapkan sebagai tenaga kerja belaka.
Dari Seremonial ke Aksi Nyata
Hari Pendidikan Nasional tidak boleh sekadar menjadi ajang slogan dan retorika belaka. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan harus bergerak menuju reformasi yang konkret.
- Distribusi anggaran pendidikan yang lebih adil, dengan fokus pada daerah tertinggal dan sekolah-sekolah marginal.
- Evaluasi kurikulum secara partisipatif, melibatkan guru dari berbagai latar belakang wilayah dan jenjang.
- Digitalisasi administrasi guru untuk mengurangi beban kerja non-pedagogis.
- Penguatan pengawasan dana BOS dan bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan bebas dari korupsi.
Dengan begitu, pendidikan bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi membentuk karakter bangsa. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak bangsa”. Jika kita ingin bangsa yang beradab dan maju, pendidikan harus menjadi prioritas yang dijalankan secara serius bukan sebatas simbolis semata.
Daftar Pustaka:
- Badan Pusat Statistik (2024). Statistik Pendidikan 2024. Jakarta: BPS.
- Kemendikbudristek (2023). Laporan Tahunan Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- OECD (2022). PISA 2022 Results. https://www.oecd.org/pisa
- Indonesia Corruption Watch (2024). Laporan Praktik Korupsi dan Pungutan di Sekolah. Jakarta: ICW.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.