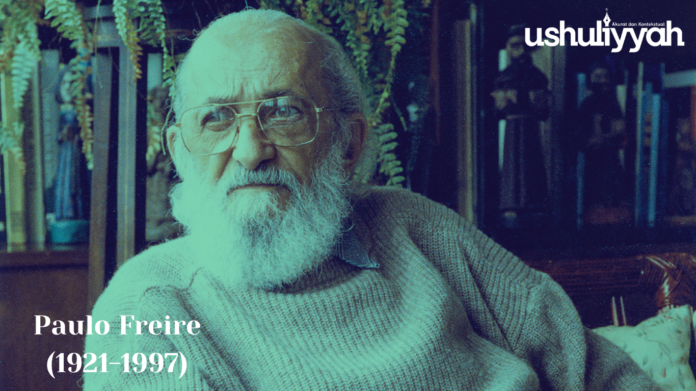Di kehidupan modern yang semakin terdigitalisasi, perlahan namun pasti. Merangkak bersama Artificial Intelligence (AI) dengan harap-harap cemas. Gemaan Tan Malaka yang di-songsong oleh beberapa anak muda yang sadar akan pentingnya “Critical Thinking” mempopulerkan madilog, sebuah akronim dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sebuah panduan bagi rakyat indonesia agar melakukan pembebasan dari akal pikiran, pernyataan-pernyataan mistik dan klenik yang begitu mengakar kuat dalam alam bawah sadar.
Melalui materialisme yang bukan sekadar mengcopas gagasan Marx, Tan Malaka ingin rakyat indoensia menghitung dan memahami kehidupannya menggunakan landasan data yang bersih dari persepsi takhayul, kemudian dialektika mengarahkan padangan materil sebelumnya kepada konflik yang tengah dirasa saat ini. Melihat perkara satu yang bertentangan atau bersanding dengan perkara lainnya, menghasilkan peristiwa yang dapat menjadi data memprediksi aksi yang bisa dilakukan. Terakhir, Logika sebuah filter memilah antara pengetahuan yang pasti dan informasi yang ditunggangi ketidakmasukakalan dan terselip pemalsuan.
Sebuah pikiran yang mengancam tidak hanya bagi penjajah jepang, saat itu juga kepada adat hierarki penjinak rakyat berstatus bawah yang digiring oleh bupati mereka sendiri untuk menjadi budak pekerja romusa. Buku yang mengajak kemandirian berpikir dan memutuskan kebijakan yang bertujuan perubahan nyata. Karena Madilog hadir sebagai “pencerah” Masyarakat Indoesia saat zaman kolonial jepang. Demi kesadaran individu dari pengekangan doktrin pembelenggu kebebassan berpikir. Madilog tidak menyusuri ruang kelas yang tanpa disadari menjadi sarang pengabaian seorang calon penerus bangsa untuk mengubah ketimpangan sosial.
Paulo Freire, seorang filosof Pendidikan Brazil menyusuri lorong-lorong kelas yang menutup kreativitas para murid dalam memunculkan solusi. Diakibatkan oleh sistem pendidikan yang diberlakukan mengandung agen penindasan. Sistem tersebut bertujuan menjinakkan anak-anak ingusan nakal dicetak sesuai dengan kebutuhan pasar para kapitalis untuk mendapat pasokan tenaga kerja dari pabrik yang ia miliki.
Mari membaca penindasan terselubung kaum penindas dari lembaran-lembaran pergulatan Freire demi pendidikan yang membebaskan.
Otak Murid Sama dengan Bank
Setelah mengabdikan hidupnya selama bertahun-tahun demi pembebesan buta huruf kaum petani di amerika latin dan sempat dipenjara karena bersinggungan dengan rezim militerisme, Freire menulis ide pembaharunya dalam “Pedagogy of the Oppressed” yang dalam versi terjemahan indonesianya berjudul, “Pendidikan Kaum Tertindas”. Friere melihat aktivitas pembelajaran dikelas ternyata sebatas transmisi ilmu pengetahuan tanpa murid benar-benar tahu “memang gunanya saya belajar itu apa?”
Pola pendidikan tradisional, memasukkan ilmu-ilmu untuk dihafalkan murid. Para murid hanya dilihat sebagai objek yang harus diluruskan, dibimbing, dan diarahkan. Dalam pola ini attitude dan kesopanan diselipkan dalam proses mengajar demi hilangnya pemberontakan dan mengamankan guru (sebagai pemilik ilmu pengetahuan) dari status terpandang berupa si pintar.
Freire menyebutnya dengan Pendidikan gaya bank. Guru seperti menabung (menyusupkan) ilmu-ilmu kedalam kepada murid. Sekolah yang bagus adalah yang mencetak lulusan-lulusan yang banyak “tabungan” kepalanya. Untuk apa? Supaya berguna di dunia kerja alias pasar. Jadi kata kunci dari model pedidikan bank ini adalah fungsionalisme, tolok ukur peringkat sekolah ada pada murid yang berlimpah pengetahuannya.
Pendidikan yang Membebaskan
Lantas, apa yang salah? Cara berpikir, “aku superior dan kamu bukan apa-apa”, yang menjadi sasaran kritik Freire. Pola pembelajaran satu arah yang mendudukan guru sebagai satu-satunya sumber otoritatif menghambat pertumbuhan kreativitas murid saat keluar dari sekolah dan memadamkan obor nalar kritis saat mendapat masalah dihadapannya.
Murid menjadi “manja” dan “konsumen” pengetahuan yang disebut berasal dari si pintar. Bukankah yang pintar harus mencerahkan mereka yang tidak tahu? Freire memasang wajah sinis mendengarnya, itu bukan pencerahan tapi penindasan! Pendidikan gaya bank dimulai dari pemahaman yang keliru dari manusia sebagai objek. Guru sama halnya dengan kaum penindas, memiliki jiwa dehumanisasi dengan mengabaikan muridnya, inilah sifat ideologi penindasan, menolak pendidikan dan pengetahuan sebagai proses dari pencarian.
Freire menyuarakan pendidikan yang membebaskan bukan pendidikan yang menindas. Basisnya adalah mencintai pertumbuhan muridnya, guru tidak menanam banyak bibit pengetahuan kedalam kepala muridnya, tapi guru memupuk tanah supaya subur dalam pertumbuhan kesadaran murid. Guru yang peduli dengan akar muridnya yang menyimpan segenap potensi dan mengalihkan perhatian murid dengan masalah-masalah yang dialami langsung oleh si murid, ini disebut dengan pendidikan hadap-masalah, mempertemukan murid pada kegiatan menelaah, memaknai, dan mengkritis serta bersama membuat solusi.
Harapannya terjadi “Conscientizacao” (konsep yang Freire buat sendiri dalam bahasa Portugis, tidak ada terjemahan Inggris maupun Indonesianya), proses dimana seseorang mulai sadar bahwa ketidakadilan dan ketimpangan tidak terjadi begitu saja. Dan manusia sebagai agen perubahan bisa, harus, dan perlu mengubahnya.
Dalam alam pikir filsuf Brazil itu, gurulah faktor penggerak bersama muridnya. Guru tidak lagi sebatas memasok ilmu kedalam kelas yang menciptakan jarak personal dengan murid-muridnya. Maka demi proses “hadap-masalah” tidak terjebak pada rasa superioritas guru, Freire mengajukan pendidikan dialogis.
Guru disamping mengelar pengajaran, dia pula menjadi murid yang tengah memahami kondisi muridnya. Dan murid memiliki status kedua, murid menjadi guru yang memberitahu gurunya atau menjelaskan kepada gurunya kondisi, pendapat, dan masukan dari murid. Jadi, “guru-murid” berdialog dengan “murid-guru” demi pemahaman dunia yang utuh.
Pemahaman bukan produk mapan yang langsung dikonsumsi, melainkan hasil ikatan kebersamaan guru dan murid. Agen perubahan adalah guru dan murid. Ini adalah gagasan radikal dan mendobrak norma pendidikan pada masanya. Lantas apa sangkut pautnya dengan luka feodal di nalar kita?
Pelajar Pasif Gara-gara Pendidikan Gaya Bank
Jadi, Pendidikan gaya bank yang terpatri dalam alam pikir kita, tentang si superior dan si inferior, memandang manusia sebelah mata. Sehingga tugas yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab dengan pola pikir malas dan mau disuapi terus menerus, memenjarakan kita dari merasakan bebasnya berinovasi, mendaya gunakan kreativitas, dan segudang keahlian terpendam dibawah alam sadar sana.
Kita adalah produk pendidikan gaya bank yang dipasok untuk terus mengerakkan roda ekonomi bangsa (belajar buat kerja), yang bisa kita lihat sendiri jumlahnya tak sebanding dengan mahasiswa fresh graduate pertahunnya. Apakah kita masih bisa mengharapkan gaya bank akan memakmurkan dan membebaskan kita dari kemiskinan, sedangkan jiwa pengemis dan menunggu diberi masih terulang di meja kampus yang menormalisasi formalitas?
Maka ibda’ binafsik (mulailah dari dirimu sendiri), dari mana? pembebasan cara pikir fatalistik akan kepastian kerja. “Madilog” Tan Malaka dan “Pedagogy of the Oppressed” Paulo Freire, menyadari ketimpangan social. Materialis yang menopang dialektika dan di filter Logika dengan Conscientizacao akan kesadaran ketimpangan dan kesadaran diri berdayanya manusia untuk mengubah yang bisa diubah dan memang harus diubah, membebaskan akal dari belenggu pencekik inovasi dan kreativitas.
Jika Marx dalam arus media sosial Kembali menjadi aktor yang mengkritik keras kapitalisme yang tidak bisa dipercaya memakmurkan dan memenjara kebebasan manusia, kenapa penjara dalam pikiran masih kita pelihara? Dan kenapa jiwa menindas kaum penindas masih menggoda kita untuk merendahkan orang tak sepemahaman? Dan diam-diam kita menyuarakan Marx dengan semu, malas belajar dan merasa aktif.