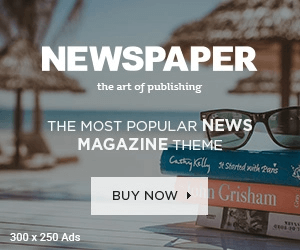Belakangan ini, perubahan cuaca menjadi lebih sulit untuk diprediksi, terutama bagi petani yang bergantung pada ketepatan musim tanam dan panen. Perubahan iklim global dan peningkatan kesadaran manusia tentang dan respons terhadap lingkungan alam adalah dua faktor yang menyebabkan fenomena ini. Petani Indonesia di masa lalu memiliki kearifan lokal yang kuat dalam membaca tanda-tanda alam yang tertanam kuat pada budaya agraris mereka. Fakta ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai standar untuk menentukan waktu terbaik untuk menanam, memanen dan melakukan tugas pertanian lainnya.
Sistem perkiraan cuaca yang menjadi budaya agraris biasa disebut “pranata mangsa” sebagai kalender musim tradisional Jawa yang menggabungkan observasi alam, pergerakan matahari, dan siklus kehidupan. Pranata mangsa merupakan salah satu bentuk pengetahuan lokal yang paling menonjol. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menghitung waktu, tetapi juga berfungsi sebagai representasi komunikasi antara manusia dan alam semesta dalam konteks kepercayaan budaya lokal.
Dalam situasi ini, pranata mangsa memiliki nilai yang signifikan sebagai warisan dari tradisi media tradisional yang menghubungkan manusia dengan petunjuk ilahi melalui bahasa alam. karena itu, penyelidikan ulang pranata mangsa menjadi penting sebagai tanggapan terhadap ketidakpastian cuaca di zaman sekarang.
Sebagaimana dijelaskan bapak Nangsir Soenanto dalam wawancara pada 15 Mei 2025 di Kulon Progo, “Pranata Mangsa bukan semata sistem penanggalan pertanian, tetapi sekaligus merupakan manifestasi kosmologi Jawa yang memandang alam semesta sebagai entitas hidup dan sakral.” Ungkapnya.
Waktu tidaklah sekadar layak dipahami seperti perjalanan linear, tetapi juga siklikal, yang mengalir dalam keselarasan antara langit, bumi, dan manusia. Tiap mangsa atau musim menimbulkan narasi simbolik mengenai hubungan batin antara manusia dan alam semesta. Rasa kehidupan ditertibkan melalui keselarasan dan simbol kepekaan terhadap tanda-tanda alam. Pranata Mangsa melampaui fungsi praktisnya sebagai pedoman pertanian untuk mengandung masyarakat rohaniah dan etis.
Didalamnya juga menuntut kebijaksanaan ilmiah untuk “membaca” alam, menunggu, dan bertindak tanda penuh kesadaran. Dalam hal ini, pranata mangsa mencerminkan filsafat Jawa yang memuja keseimbangan antara seimbang manusia dan semesta. Dalam tekanan modern seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, menggali kembali makna filosofis dalam pranata mangsa bukan hanya sebagai warisan yang mesti dijaga, tetapi sebagai prinsip dalam membangun cara berhubungan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan dengan alam.
Falsafah Jawa biasa disebut “Sedulur Papat Limo Pancer” yang merupakan pandangan mengenai keberadaan manusia dengan alam, spiritual dan masyarakat. Dalam pandangan ini zat awal kehidupan berawal dari unsur-unsur dasar seperti api, air, tanah dan udara yang membentuk sistem kehidupan manusia. Setiap unsur dasar memiliki hubungan dengan nafsu yang setiap bagiannya saling terkait seperti, nafsu Lawwamah berkaitan dengan Supiah dan Mutmainnah dengan Amarah. Hubungan tersebut menjadi dasar kehidupan yang seimbang yang di cerminkan pada sturktur Pranata mangsa.
Dalam perhitungan waktunya termasuk hari dan pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon) yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan aktivitas petani. Setiap hari dan pasaran membentuk siklus 35 hari. Contoh, Senin legi, Selasa Pahing, Rabu Pon, Kamis Kliwon dan seterusnya. Tahun pada pranata mangsa dimulai setiap 22 juni dan terdiri dari 12 mangsa dan masing-masing memiliki durasi yang tidak sama.
Antara Supranatural dan Pengetahuan
Pranata Mangsa sering disebut ilmu warisan yang dikaitkan dengan hal-hal mistis atau supranatural, terutama dalam budaya lokal yang kental dengan tradisi leluhur. Namun, tidak semua ilmu warisan bersifat gaib. Banyak ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi bersifat logis dan sangat berguna dalam kehidupan nyata.
Misalnya, ilmu pengobatan tradisional. Seorang nenek di desa bisa tahu tanaman mana yang menyembuhkan luka atau menurunkan demam. Pengetahuan ini bukan hasil bisikan gaib, tetapi dari pengalaman bertahun-tahun mengamati, mencoba, dan mencatat hasilnya meski hanya dalam ingatan. Contoh lain seperti ilmu pertanian lokal, petani tradisional bisa memprediksi cuaca hanya dengan melihat perilaku hewan atau bentuk awan.
Mereka tidak punya satelit atau aplikasi cuaca, tapi punya logika yang dibangun dari observasi yang konsisten. Jadi, ilmu warisan tidak selalu mistis. Banyak yang bersifat empiris dan ilmiah, hanya saja belum dibukukan secara akademis. Melestarikannya berarti menjaga kebijaksanaan lokal yang terbukti efektif secara logis dan praktis.
Meskipun hidup di era modern yang dipenuhi teknologi canggih, sebagian masyarakat Jawa, terutama yang tinggal di pedesaan dan bergelut dalam sektor pertanian, masih mempertahankan penggunaan pranata mangsa. Sistem penanggalan tradisional ini dianggap memiliki akurasi tersendiri dalam membaca tanda-tanda alam dan menentukan waktu yang tepat untuk bertani, seperti masa tanam, pemupukan, hingga panen.
Pengalaman turun-temurun menjadikan pranata mangsa lebih dari sekadar kalender, ia menjadi pengetahuan lokal yang hidup dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi cuaca modern, seperti aplikasi prakiraan cuaca, sensor kelembaban tanah, dan citra satelit, telah mengubah cara petani mengelola lahannya. Di sinilah terjadi kombinasi menarik, sebagian petani memilih menggabungkan informasi dari pranata mangsa dengan teknologi cuaca modern. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.
Relevansi pranata mangsa di era modern justru semakin tampak ketika ia tidak diposisikan sebagai pesaing teknologi, tetapi sebagai pelengkap, menjadi wujud nyata kearifan lokal yang tetap dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global, seperti krisis iklim dan degradasi lingkungan. Dengan mempertahankan pranata mangsa, masyarakat bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional masih mampu berdialog dengan zaman.
Kritik Transfer Pengetahuan Lintas Zaman
Pranata mangsa menjadi suatu sistem penghitungan musim dari Jawa yang dulu digunakan para petani untuk menentukan waktu menanam dan memanen. Pengetahuan ini dulu disampaikan secara lisan, tetapi sekarang hampir tidak dikenal oleh generasi muda. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah kurikulum pendidikan yang kurang memperhatikan kearifan lokal. Sekolah-sekolah lebih banyak memfokuskan pada ilmu pengetahuan modern dan global, sehingga budaya serta pengetahuan tradisional sering kali terabaikan.
Generasi muda tumbuh tanpa pemahaman yang mendalam tentang warisan budaya dari nenek moyang mereka. Proses modernisasi dan perubahan budaya juga berperan dalam mempercepat hilangnya pengetahuan tradisional ini. Teknologi serta budaya pop dari luar dianggap lebih menarik dan relevan, sedangkan tradisi lokal dipandang sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan tidak praktis.
Situasi ini berakibat pada terputusnya transfer pengetahuan antar generasi. Jika tidak ada langkah konkret untuk melestarikan melalui pendidikan, dokumentasi, atau revitalisasi, maka pengetahuan seperti pranata mangsa bisa sepenuhnya punah. Sementara itu, dalam pengetahuan tersebut tersimpan nilai-nilai ekologis, sosial, dan budaya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat.