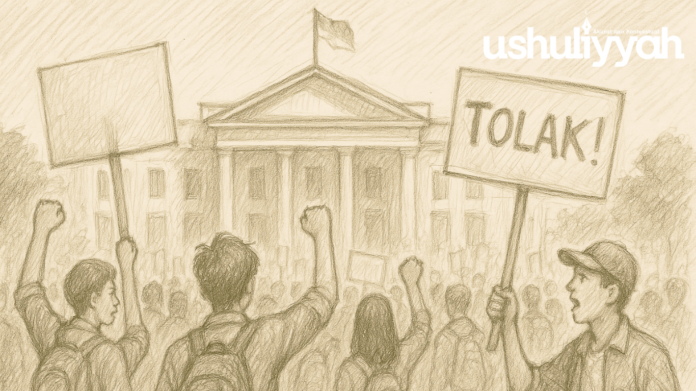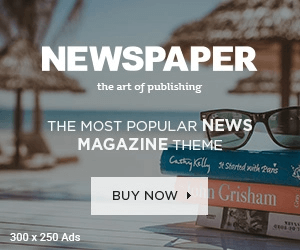Indonesia hari ini seperti televisi tua yang dipaksa menampilkan tayangan modern, layarnya buram, suaranya sumbang, dan salurannya tak lagi nyambung dengan kenyataan rakyat. Negara salah channel, alih-alih menyiarkan keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan, yang tayang justru episode berulang, korupsi berjamaah, nepotisme terang-terangan, dan peminggiran suara kritis. Ketika tayangan negara sudah tidak relevan dengan realitas rakyat, maka mahasiswa, seperti biasa, memilih ganti frekuensi.
Frekuensi mahasiswa bukan disiarkan dari istana, bukan pula dari gedung DPR. Ia lahir dari keresahan, dibentuk oleh ketidakadilan, dan disuarakan melalui poster, orasi, serta jejak langkah kaki di jalanan. Mahasiswa tidak menonton, mereka menantang. Mereka tidak menunggu pergantian acara, mereka menciptakan gelombang sendiri. Ini bukan soal heroisme murahan, ini soal tanggung jawab sejarah.
Negara hari ini tampak sibuk. Sibuk menambal reputasi, bukan memperbaiki sistem. Sibuk membungkam kritik, bukan mendengar aspirasi. Sibuk mengatur narasi, bukan mengakui realitas. Lembaga-lembaga negara bertransformasi menjadi pusat produksi citra, bukan lagi pelayan publik. Presiden yang dulu dielu-elukan sebagai figur perubahan kini tak segan memasukkan keluarga dalam sistem kekuasaan. Para Dewan lebih sibuk menjadi stempel pengesahan undang-undang pesanan korporasi ketimbang memperjuangkan suara rakyat.
Layar demokrasi kita penuh distorsi. Hukum tayang eksklusif untuk kaum elit, sementara rakyat kecil hanya muncul sebagai latar penderitaan. Kebijakan publik disulap menjadi konten yang enak dilihat, padahal substansinya cacat. UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodasi syahwat politik keluarga penguasa adalah beberapa contoh bagaimana negara kehilangan arah siarannya.
Indonesia sedang berada di titik genting demokrasi. Negeri yang dibangun di atas semangat reformasi dan cita-cita keadilan sosial kini kembali dibajak oleh elitisme politik, pembungkaman suara kritis, dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin terang-terangan. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya kekuatan moral yang tersisa adalah mahasiswa, generasi yang tak hanya belajar di ruang kuliah, tetapi juga turun ke jalan untuk menjaga akal sehat bangsa.
Aksi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” yang belakangan ini menggema di berbagai kota bukanlah sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah penanda bahwa dalam gelapnya situasi sosial-politik tanah air, masih ada yang mau menyalakan cahaya, meskipun hanya lewat korek kecil bernama idealisme.
Mahasiswa kembali hadir sebagai suara kritis di tengah masyarakat yang makin dicekik oleh berbagai tekanan. Isu kenaikan biaya hidup, ketimpangan kebijakan, dan pudarnya transparansi publik menjadi dasar keresahan yang tak bisa terus diredam dengan dalih stabilitas. Justru dari keresahan inilah aksi bermula dengan poster-poster buatan tangan sendiri, orasi-orasi lantang, serta semangat yang tak digaji.
Di sisi lain, mahasiswa juga menunjukkan bahwa perjuangan tak harus selalu mewah. Mereka bergerak tanpa fasilitas, tanpa kamera mewah, bahkan tanpa jaminan aman. Namun justru dari kesederhanaan itulah muncul ketulusan. Aksi mereka menjadi bukti bahwa demokrasi masih bernyawa meski mungkin dalam tubuh yang lelah.
Sayangnya, respons sebagian elite justru defensif. Kritik dianggap sebagai upaya menjatuhkan. Lembaga legislatif telah kehilangan jiwanya sebagai wakil rakyat. Alih-alih memperjuangkan aspirasi publik, mereka sibuk mengesahkan undang-undang yang cacat prosedur, tidak partisipatif, dan sarat kepentingan oligarki. Dari UU Cipta Kerja yang lahir lewat metode “patgulipat legislasi”, hingga revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah, publik dipaksa menelan kebijakan yang menjauh dari keadilan.
Lembaga eksekutif pun tak kalah buruk. Presiden yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perubahan justru menjelma menjadi simbol kompromi politik. Penempatan anak dan menantu dalam jabatan strategis menunjukkan bahwa nepotisme bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, melainkan dirayakan secara terang-terangan. Di tengah krisis kepercayaan publik, pemerintah lebih sibuk membangun pencitraan ketimbang menyelesaikan masalah mendasar seperti pengangguran, kemiskinan struktural, dan ketimpangan akses pendidikan.
Sementara itu, lembaga yudikatif tidak lagi menjadi benteng terakhir keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden yang diduga sarat konflik kepentingan keluarga mengoyak kredibilitas lembaga yang seharusnya netral. Rakyat melihat langsung bagaimana hukum bisa ditekuk untuk mengamankan kekuasaan segelintir orang.
mengerikan lagi adalah tren pembungkaman kebebasan berekspresi. Aktivis ditangkap, dosen dikriminalisasi karena menyampaikan kritik, jurnalis diintimidasi, dan mahasiswa yang turun ke jalan dicap sebagai perusuh. Pemerintah dan aparat tak segan menggunakan kekerasan untuk memadamkan protes. Ini bukan lagi negara demokrasi; ini negara yang alergi terhadap suara berbeda.
Media arus utama pun tak luput dari tekanan. Banyak yang memilih bungkam atau menyajikan berita dengan framing pro-pemerintah demi menjaga relasi bisnis dan izin usaha. Media sosial yang semula menjadi ruang bebas berekspresi, kini dipantau ketat, bahkan kerap dijadikan dasar pemidanaan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi senjata ampuh negara untuk menakuti warganya.
Dalam kondisi gelap gulita seperti ini, mahasiswa kembali menjadi lilin yang menyala di tengah kegelapan. Mereka turun ke jalan, menentang ketidakadilan, menyuarakan yang tidak bisa disuarakan oleh rakyat biasa. Aksi-aksi seperti Reformasi Dikorupsi (2019), gelombang penolakan Omnibus Law, hingga protes terhadap pelemahan KPK menunjukkan bahwa mahasiswa tidak diam. Mereka hadir, lantang, dan bersedia dibenturkan dengan kekuasaan demi idealisme.
Demonstrasi bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang mati rasa. Di tengah ketakutan kolektif, mahasiswa membuktikan bahwa keberanian tidak lahir dari kekuatan fisik, tetapi dari kemurnian nurani. Ketika pemerintah memandang kritik sebagai ancaman, mahasiswa hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan bukan warisan, melainkan mandat.
Seringkali, mahasiswa dituduh sebagai pengacau, perusak fasilitas, atau digambarkan sebagai pihak yang tak tahu apa-apa soal pemerintahan. Namun sejarah mencatat, reformasi 1998 bukan hasil rapat kabinet, melainkan jeritan mahasiswa di jalanan. Demokrasi yang kita nikmati betapapun pincangnya hari ini dibayar dengan darah dan air mata para pemuda yang berani melawan rezim otoriter.
Lebih dari itu, aksi mahasiswa sering kali menjadi momentum bagi publik untuk mengingat bahwa demokrasi adalah ruang bersama. Ketika ruang itu dipersempit, suara-suara pinggiran akan mencari jalan sendiri untuk didengar.
Tidak bisa dipungkiri, keresahan yang disuarakan mahasiswa adalah cerminan jeritan masyarakat luas. Para petani kehilangan lahan, buruh menjerit karena upah tak sepadan, mahasiswa sendiri tercekik oleh biaya pendidikan yang terus merangkak naik. Ini bukan keluhan sektoral, tapi mozaik kegelisahan nasional yang belum ditangani dengan serius.
Kita juga patut mempertanyakan: mengapa aksi semacam ini muncul berulang? Bukankah itu pertanda bahwa ada hal-hal yang belum juga berubah? Atau justru ada yang berubah, namun tak sesuai harapan? Ketika mahasiswa merasa perlu turun ke jalan berkali-kali, itu artinya dialog formal tak lagi cukup. Mereka tidak bergerak karena benci negara, tapi karena masih percaya negeri ini bisa lebih baik.
Tentu, gerakan mahasiswa bukan tanpa cela. Mereka tetap butuh arah, strategi, dan keberlanjutan. Namun dibanding sikap apatis dan diam, keberanian turun ke jalan adalah pilihan yang layak dihormati. Negara ini tidak kekurangan masalah, tapi kadang kekurangan keberanian untuk mengakuinya. Mahasiswa hadir bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk mengingatkan, bahwa di balik angka-angka makro-ekonomi, ada rakyat yang sedang mengencangkan ikat pinggang.
Kini, sejarah memanggil kembali. Ketika pemerintahan menjauh dari rakyat dan mendekat pada kapital, ketika kebijakan publik menjadi alat barter politik, dan ketika kebenaran menjadi barang langka, mahasiswa punya tanggung jawab untuk menegakkan kembali marwah bangsa. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian menyampaikan kebenaran.
Namun tantangan ke depan lebih kompleks. Gerakan mahasiswa tak cukup hanya dengan aksi sporadis dan seruan emosional. Diperlukan strategi, konsolidasi, dan kejelasan tuntutan. Mahasiswa harus mampu membangun aliansi lintas kampus, terhubung dengan organisasi masyarakat sipil, serta mendesain narasi tanding terhadap propaganda negara.
Kritik tanpa arah akan mudah dimentahkan. Sebaliknya, gerakan yang terorganisir dengan baik, berbasis data, dan memiliki visi kebangsaan akan menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Mahasiswa bukan hanya agen perubahan, mereka adalah cermin bangsa. Jika mereka rapuh, maka rapuhlah masa depan Indonesia.
Jika kegelapan ini terus dibiarkan, maka bangsa ini hanya akan menunggu waktu untuk tersandung. Tapi jika cahaya kecil mahasiswa diberi ruang, bukan tidak mungkin jalan keluar akan tampak. Sebab, terang bukan hanya datang dari kekuasaan, tapi dari siapa saja yang berani melawan gelap.
Indonesia sedang gelap bukan karena tidak ada cahaya, tetapi karena terlalu banyak yang memilih untuk memadamkannya. Mahasiswa datang bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk mengingatkan bahwa negeri ini masih punya harapan. Mereka adalah saksi sejarah yang menolak lupa, dan pelaku sejarah yang tidak tinggal diam.
Di tengah arogansi kekuasaan dan apatisme publik, keberanian mahasiswa adalah napas terakhir demokrasi. Maka, jangan pernah remehkan suara mereka. Karena di balik orasi dan poster, tersimpan tekad untuk mengubah arah bangsa menuju Indonesia yang lebih adil, jujur, dan bermartabat.